Serakahnomics: Rakyat Tanpa Kuasa
Sabtu, 02 Agustus 2025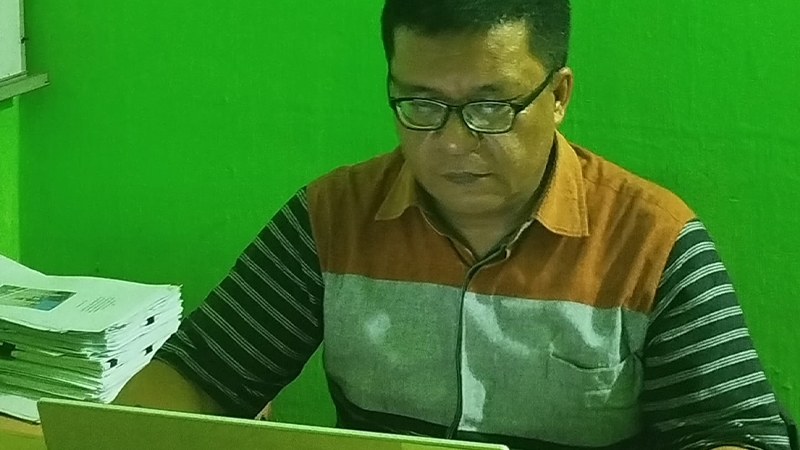
DALAM forum The 28th St Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025) Presiden Prabowo Subianto berpidato: “Ada bahaya di negara berkembang seperti Indonesia, (yakni) kolusi antara pemodal besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik, kolusi yang tidak membuahkan hasil pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah”.
Pernyataan yang senada dengan bukunya Paradoks Indonesia (2017), Prabowo juga menulis: "Indonesia kaya, tapi rakyat kita banyak yang lapar." yang menyoroti ironi bahwa negara yang kaya akan sumber daya justru memiliki rakyat yang hidup dalam kekurangan".
Terakhir dalam pidatonya pada penutupan Kongres PSI, 20 Juli 2025, Presiden Prabowo memperkenalkan serakahnomics: "Ini ada mazhab baru ekonomi, itu yang saya sebut mazhab serakahnomics. Ini ilmu serakah, sudah dikasih, minta lagi, sudah dikasih dua, minta empat. sudah dikasih empat, minta delapan..."
Serakahnomics yang menggambarkan kondisi akut, dimana segelintir pelaku usaha, pejabat dan pemegang kekuasaan ekonomi-politik menumpuk kekayaan negara untuk kepentingan sendiri tanpa batas moral, sebuah sistem yang menyingkirkan aspirasi dan kepentingan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
Ketimpangan ekonomi Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Laporan Credit Suisse (2018) menyebut bahwa 1% orang terkaya Indonesia menguasai 44,6% kekayaan nasional.
Sementara 60% penduduk hanya mengakses 15% dari total kekayaan, tentunya ini bukan hanya angka, tetapi realitas hidup yang terasa setiap hari.
Namun, setelah sembilan bulan menjabat sebagai Presiden, situasi belum menunjukkan perbaikan berarti, kesenjangan ekonomi tetap tajam, harga kebutuhan pokok terus naik, dan rakyat belum merasakan janji yang diucapkan dalam pidato, sebaliknya, yang terjadi justru penguatan cengkeraman kekuasaan dan modal atas ruang hidup rakyat.
Serakahnomics : Politik dan Ekonomi yang Dikuasai Segelintir Orang
Serakahnomics tidak muncul tiba-tiba, namun lahir dari perkawinan antara kekuasaan politik dan kekuatan modal. Bisa melalui pendanaan kampanye politik, yang berbalas jasa dalam bentuk proyek infrastruktur, konsesi lahan atau kebijakan yang menguntungkan bisnis pemilik modal, perkawinan yang menciptakan lingkaran oligarki dengan memperlemah kontrol rakyat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat bahwa sektor vital seperti energi, pangan, dan konstruksi dikuasai oleh segelintir konglomerat.
Bahkan ada asumsi, harga tidak lagi ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi oleh kesepakatan para pelaku besar, yang berakibat rakyat harus membayar mahal untuk kebutuhan dasar, sementara keuntungan mengalir ke kantong para elite ekonomi politik.
Biaya politik yang mahal sering memaksa politisi mencari sponsor dari kalangan pemodal, tidak sedikit cerita yang menyebutkan bahwa dana kampanye para peserta pemilu dibiayai oleh donatur besar yang memiliki kepentingan bisnis langsung.
Kondisi yang berdampak pada perilaku politisi yang cenderung melayani kepentingan penyumbangnya ketimbang konstituen, akhirnya banyak kebijakan, bukan dilahirkan dari aspirasi publik, melainkan dari lobi-lobi tertutup dengan pihak berkepentingan.
Walaupun pemilu digelar secara periodik, namun demokrasi electoral yang marak dengan politik uang dan bungkus bantuan sosial, telah membuat pemilu kehilangan jiwa, karena dianggap menjadi pasar transaksional yang mahal dan penuh tipu daya.
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) Mei 2025 merilis persepsi publik atas optimisme dan kinerja pemerintah. Dengan kepuasan terbawah dari 15 lembaga negara adalah DPR (45,8%) dan partai politik (43%) yang merupakan produk dan peserta pemilu.
Kondisi yang memberikan gambaran bahwa suara DPR dari partai politik tidak lagi dianggap sebagai penyambung kepentingan rakyat, namun telah berubah menjadi sekadar prosedur menduduki jabatan tanpa substansi.
Partai politik, yang seharusnya menjadi perantara rakyat dan negara, kini didominasi elite politik yang tak memiliki akar kuat di masyarakat, hal ini terlihat dari komposisi anggota DPR RI 2024–2029 yang 60% ( 354 dari 580 Orang ) terafiliasi dengan grup bisnis ( ICW ).
Komposisi yang tentunya melahirkan dugaan dan asumsi dalam penentuan arah kebijakan, termasuk jika melihat proses koalisi partai, yang dibentuk seringkali bukan atas dasar visi misi, melainkan kalkulasi kekuasaan.
Maka tidak heran, meskipun berganti pemimpin, arah kebijakan tetap, tidak banyak berubah, karena dikendalikan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
Situasi yang diperburuk oleh banyaknya organisasi rakyat, organisasi non pemerintah, dan intelektual yang dulu kritis kini justru bungkam atau bahkan terkooptasi.
Organisasi non pemerintah yang dulunya kritis, mungkin lebih memilih jalur aman bekerja sama dengan pemerintahan. Begitu juga intelektual dan akademisi memilih diam karena bisa berdampak pada posisi atau akses.
Dari berbagai pergolakan dalam 10 tahun terakhir, tidak banyak dosen di perguruan tinggi yang bersuara mengenai isu ketimpangan praktik hukum, ekonomi dan politik.
Sedangkan mahasiswa yang dulu menjadi motor perubahan kini lebih banyak terjebak dalam pragmatisme organisasi atau keraguan terhadap efektivitas gerakan dalam medorong perubahan untuk mencapai amanat konstitusi.
Organisasi sektoral juga seolah terfragmentasi. Mereka lebih sibuk pada kegiatan seremonial. Padahal di tengah tingginya ketimpangan, rakyat membutuhkan perlindungan dan representasi yang kuat.
Ketika organisasi rakyat, lembaga non pemerintah dan intelektual bungkam, maka tidak akan ada lagi rem terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan.
Dalam sektor pendidikan, ketimpangan juga nyata. Masih banyak anak yang putus sekolah, karena harus membantu ekonomi keluarga.
Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang naik setiap tahun, namun beasiswa tetap terbatas dengan mendasarkan pada data DTKS Kemensos yang menggunakan standart kemiskinan pengeluaran dibawah Rp. 20.000/hari.
Di bidang kesehatan, akses terhadap layanan dasar dan mutu layanan tetap saja masih menjadi permasalahan. Mulai persoalan mutu dokter dan peralatan yang timpang, RS yang masih dikelola secara birokratis, lambat, dan layanan kurang humanis yang menyebabkan banyak pasien (PBI BPJS) mengeluh diperlakukan sebagai “objek administratif” bukan sebagai manusia yang butuh empati.
Sementara layanan di negara tetangga menawarkan pelayanan cepat, diagnosis akurat, teknologi canggih, dan kenyamanan setara hotel, dengan biaya tak jauh berbeda.
Hal ini menyebabkan kebocoran devisa hingga miliaran dolar tiap tahun, sekaligus mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar warganya atas layanan kesehatan yang layak, adil dan beradab.
Mengembalikan Kuasa Rakyat
Dalam Konstitusi dan prinsip Republikanisme, tentunya tidak membolehkan rakyat terus menjadi penonton dalam panggung kekuasaan yang dimainkan oleh segelintir orang. Karena seharusnya kuasa politik dan ekonomi harus diarahkan pada kepentingan pemilik mandat yaitu publik.
Melihat kondisi DPR dan Partai Politik, sudah selayaknya para intelektual, akademisi, organisasi non pemerintah melakukan kembali pendidikan politik yang membumi—bukan hanya di ruang kelas, tetapi di pasar, desa, dan media sosial, melalui kerjasama dengan komunitas, tokoh lokal, dan media independen.
Sehingga dalam Pemilu, rakyat sangat tahu siapa yang dipilih dan dampaknya terhadap kehidupannya, karena pilihannya sangat menentukan kualitas kehidupannya.
Saat ini yang dibutuhkan adalah kesadaran membangun kekuatan politik alternatif di luar partai politik, sebagai tenaga pemberi tekanan kolektif dari bawah untuk memaksa negara mendengar kebutuhan publik.
Dunia kampus dan kaum intelektual juga harus mengambil posisi. Tidak lagi seolah netral dalam menghadapi ketidakadilan.
Pengetahuan harus dipakai untuk membela yang lemah, bukan untuk merasionalisasi kekuasaan. Media independen dan jurnalisme warga perlu didukung untuk mengabarkan kebenaran yang tersembunyi oleh propaganda dan pengalihan issu oleh aparatus negara.
Semuanya merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan diri rakyat pada kekuatannya sendiri. Karena perubahan besar dalam sejarah selalu lahir dari keberanian rakyat untuk berkata “cukup”, dari suara-suara kecil yang bersatu dan menjadi gelombang yang mampu mengoreksi kekuasaan.
Seperti kata Bung Karno, “Bangsa yang besar bukan yang paling banyak penguasanya, tetapi yang paling kuat keberanian rakyatnya untuk berkata tidak terhadap ketidakadilan”.
Demokrasi sejati bukanlah demokrasi prosedural semata, tetapi demokrasi substantif: yang berpihak pada rakyat, memberi ruang partisipasi, dan menegakkan keadilan, bukan demokrasi yang menciptakan jurang antara penguasa (penerima mandat) dan yang dikuasai (pemberi mandat), antara kenyataan dan harapan.
Berbagai pernyataan Presiden Prabowo sudah seharusnya menjadi dasar perubahan kebijakan, bukan sekadar slogan.
Jika benar ingin rakyat sejahtera, maka arah kebijakan harus berpihak pada distribusi asset dan potensi ekonomi pada masyarakat, bukan terkosentrasi pada golongan.
Menekan serakahnomics hanya dengan menghentikan warga sebagai objek kebijakan, tetapi menjadikannya rakyat sebagai kuasa negara.
Penulis Penggiat HAM dan Demokrasi








