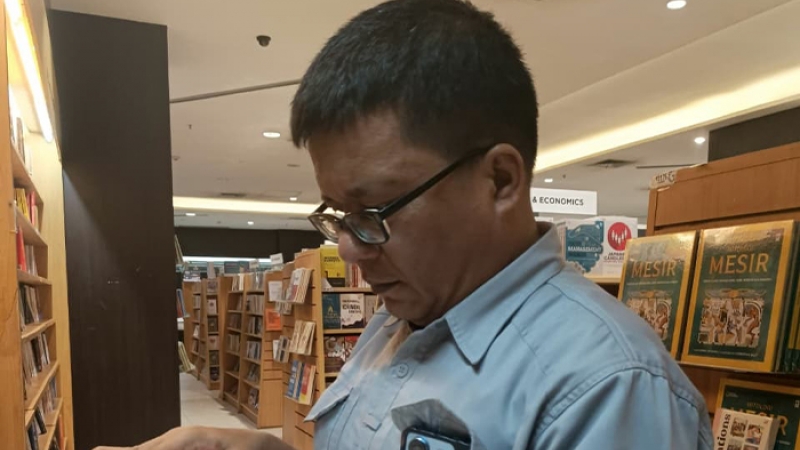Menyelamatkan Republikanisme
Sabtu, 19 Juli 2025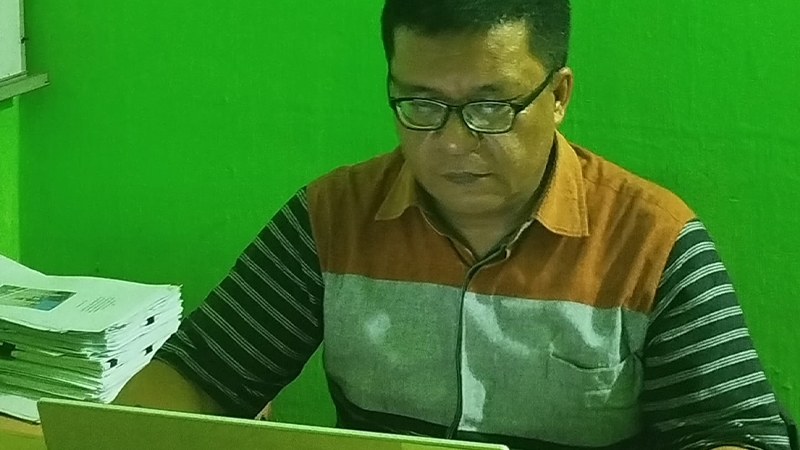
INDONESIA tidak dilahirkan sebagai monarki, tapi dalam bentuk republik. Pilihan yang diambil pada 18 Agustus 1945, pilihan di tengah perdebatan federalisme dan kekuasaan lokal.
Para pendiri memilih bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebagai mimpi bahwa tak akan ada lagi kekuasaan berdasarkan darah, kasta, ataupun warisan. Setiap warga negara punya kedudukan yang sama di hadapan hukum dan kekuasaan.
Menjelang 80 tahun, semangat republikanisme ternyata terus menyusut, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Pemerintahan seperti ladang subur politik dinasti, nepotisme dan lingkaran elite, wajah republik yang berjalan tanpa jiwa. Institusinya masih ada, konstitusinya masih dibaca, tapi ruhnya hilang entah kemana.
Falsafah politik pemerintahan berbentuk republik yang mengusung tiga nilai utama: kebajikan publik (civic virtue), partisipasi warga (civic participation), dan supremasi hukum (rule of law).
Seharusnya falsafah ini termanifestasikan dalam jabatan yang amanah untuk melayani warga. Kekuasaan dijalankan oleh dan untuk rakyat, berlandaskan prinsip kebajikan publik, partisipasi warga, dan supremasi hukum.
Namun, semua prinsip dan falsafah politik itu justru semakin langka. Hal ini akibat dari dinasti politik, politik uang, degradasi partai politik, serta kebungkaman kampus dan intelektual, yang menjadikan republik hanya sekadar nama.
Contoh nyata penyimpangan nilai republikanisme terlihat dalam kekuasaan nasional dan lokal yang dikuasai oleh segelintir elite dan keluarga politik. Ketimpangan pembangunan, kemiskinan yang tak kunjung surut, serta meningkatnya kriminalitas yang menjadi gejala runtuhnya substansi republik.
Titik Nadir Republikanisme
Dalam dokumen kenegaraan dan konstitusi, Indonesia menganut prinsip republik. Kata yang berasal dari kata Latin "res publica," yang berarti kepentingan umum. Sangat berbeda dari kerajaan atau kekuasaan otoriter yang berakar pada garis keturunan.
Tapi dalam praktiknya menjelang 80 tahun kemerdekaan, republik saat ini tak lebih dari monarki electoral. Kekuasaan politik diwariskan dari ayah ke anak, dari saudara ke ipar, dari suami ke istri, dari keluarga ke kroni.
Partai politik sebagai pondasi utama sistim demokrasi dalam bingkai republik dianggap atau diasumsikan gagal. Parpol tidak lagi berfungsi sebagai arena artikulasi kepentingan publik atau pengaderan pemimpin rakyat.
Parpol seolah menjadi toko penyewaan perahu untuk maju sebagai calon bupati, wali kota, atau gubernur dan pejabat publik. Harus membayar “mahar” politik dengan uang atau hubungan kepentingan
Kondisi yang mematikan meritokrasi regenerasi politik, karena banyaknya calon pejabat publik yang diusung adalah yang memiliki modal besar atau hubungan keluarga dengan elite penguasa,.
Jabatan publik tak lagi ditentukan oleh kapasitas. Kekuasaan seolah diwariskan secara informal dalam lingkaran keluarga. Sebuah fenomena pengkhianatan terhadap republikanisme dan bentuk pengabaian terhadap keadilan sosial.
Dominan yang muncul bukanlah pemimpin terbaik untuk rakyat, melainkan pebisnis, pemilik tambang, atau kerabat penguasa sebelumnya. Sebuah pola regenerasi kekuasaan yang dikemas dengan uang, pengaruh birokrasi, dan bantuan logistik.
Provinsi Sumatera Utara, dimana data BPS Sumut (2024) mencatat kemiskinan masih berada di angka 7,19% atau sekitar 1,11 juta jiwa, dengan tertinggi Nias Utara yang mencapai 21,7%. Tajamnya ketimpangan pembangunan tercermin dari gini ratio Sumatera Utara yang mencapai 0,306.
Kemiskinan yang berkorelasi pada angka kriminalitas terlihat dari data Polda Sumut 2023. Tercatat lebih dari 45.413 kasus kriminal dalam setahun, sedangkan Januari – Juni 2025 ada 2.373 kasus narkoba.
Belum lagi kasus pencurian, kekerasan dan premanisme yang seolah menjadikan daerah padat seperti Medan dan Deli Serdang mendapat sebutan “Gotham City“, kota kejahatan di film fiksi Batman.
Lemahnya supremasi hukum dan minimnya rasa keadilan publik juga terlihat dari fenomena "no viral, no justice" dan "percuma lapor polisi". Ini cerminan krisis kepercayaan yang semakin dalam. Banyak kasus hukum yang baru ditindaklanjuti setelah menjadi viral di media sosial.
Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi berpijak pada asas keadilan dan persamaan di hadapan hukum, namun seberapa besar tekanan publik yang menyertainya. Praktik industri hukum dianggap tumbuh subur dalam bentuk "jual beli perkara".
Yang lebih menyedihkan, masyarakat mulai menerima itu sebagai hal lumrah. Demokrasi dikooptasi oleh logika kekeluargaan dan kenormalan uang.
Partisipasi rakyat direduksi jadi aktivitas pencoblosan, bukan pengawasan dan pengendalian kekuasaan. Suara rakyat sekadar menjadi perpanjangan tangan elite, bukan lagi kekuatan korektif.
Sunyinya suara dunia akademik di tengah kerusakan republik. Kampus-kampus yang dulu menjadi pusat kritik dan penyadaran kini ikut tenggelam dalam proyek dan perburuan akreditasi.
Banyak dosen dan peneliti lebih sibuk menjadi konsultan pemda daripada menjadi pengkritik kekuasaan. Intelektual berubah menjadi "tukang", sekadar menyumbangkan legalitas akademik atas kebijakan bahkan pembenar tindakan kekuasaan.
Kritik dianggap mengganggu kerja sama dengan pemda. Tidak banyak akademisi yang bersedia mengangkat suara untuk membongkar praktik politik uang, dinasti kekuasaan, atau manipulasi pembangunan.
Ini yang disebut Gramsci sebagai “intelektual organik yang gagal”, mereka yang justru melanggengkan struktur penindasan karena memilih kenyamanan. Kaum terpelajar membisu, publik kehilangan arah, dan publik kehilangan moral kolektifnya.
Kondisi yang menyebabkan stagnasi kebijakan publik. Program strategis daerah hanya menjiplak kebijakan pusat tanpa kontekstualisasi. Pembangunan tidak menjawab kebutuhan lokal.
Seperti keseragaman program ketahanan pangan di banyak wilayah yang tidak menyentuh pola produksi dan ekonomi lokal. Bantuan sosial tersentralisasi pada alat ukur pemerintah pusat tanpa melihat standar kebutuhan hidup yang berbeda tiap daerahnya.
Ini bukan sekadar kegagalan teknokratis, tapi bukti bahwa rakyat telah tersingkir dari proses perumusan dan pengambilan keputusan publik.
Bandingkan semua ini dengan cita-cita UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Dalam praktik politik hari ini, kedaulatan itu telah dicuri pelan-pelan. Paprol menolak membuka ruang kaderisasi yang meritokratik. Elite politik menjadikan rakyat sebagai alat, bukan subjek politik. Konstitusi yang menjamin keadilan dan kesetaraan hanya hidup di teks, tidak dalam tindakan.
Republik adalah janji kebangsaan. Janji itu telah dilanggar setiap hari oleh dinasti yang berkuasa, partai yang oportunis, birokrasi yang transaksional, dan intelektual yang kompromistis.
Indonesia hidup dalam bangkai republik dalam bentuk kulitnya, tapi kehilangan ruh didalamnya.
Menemukan Kembali Republikanisme
Menyelamatkan republikanisme tentu bukan kerja satu tahun. Harus dimulai dengan keberanian mengakui bahwa krisis hari ini bukan sekadar soal pembangunan yang timpang, melainkan kebangkrutan moral dan degradasi pilar republikanisme.
Banyak lembaga demokrasi kehilangan fungsi karena telah dibajak oleh elitisme, pragmatisme, dan transaksi jangka pendek, serta menjadi perantara eksklusif bagi dinasti politik dan kelompok bermodal,.
Poses pendidikan politik publik hanya diisi perdebatan jubir politik di media dan agregasi publik dihitung melalui kalkulasi kepentingan kekuasaan
Pendidikan politik harus dikembalikan ke ruang publik, kampus, sekolah, media lokal, dan komunitas, bukan pada lembaga demokrasi formal yang bekerja formalitas semata.
Paling mendasar adalah intelektual dan kampus harus kembali menjadi pengawas kekuasaan, bukan pelayan proyek kekuasaan.
Republik hanya akan hidup jika masyarakat berani menuntut keadilan, bukan sekadar menerima keadaan dan memilih terus diam saat kedaulatan disandera kekuasaan, menghentikan suara publik yang digantikan oleh suara uang, serta mengoreksi kebijakan yang tidak taat pada tujuan kemerdekaan.
Penulis Penggiat HAM dan Demokrasi