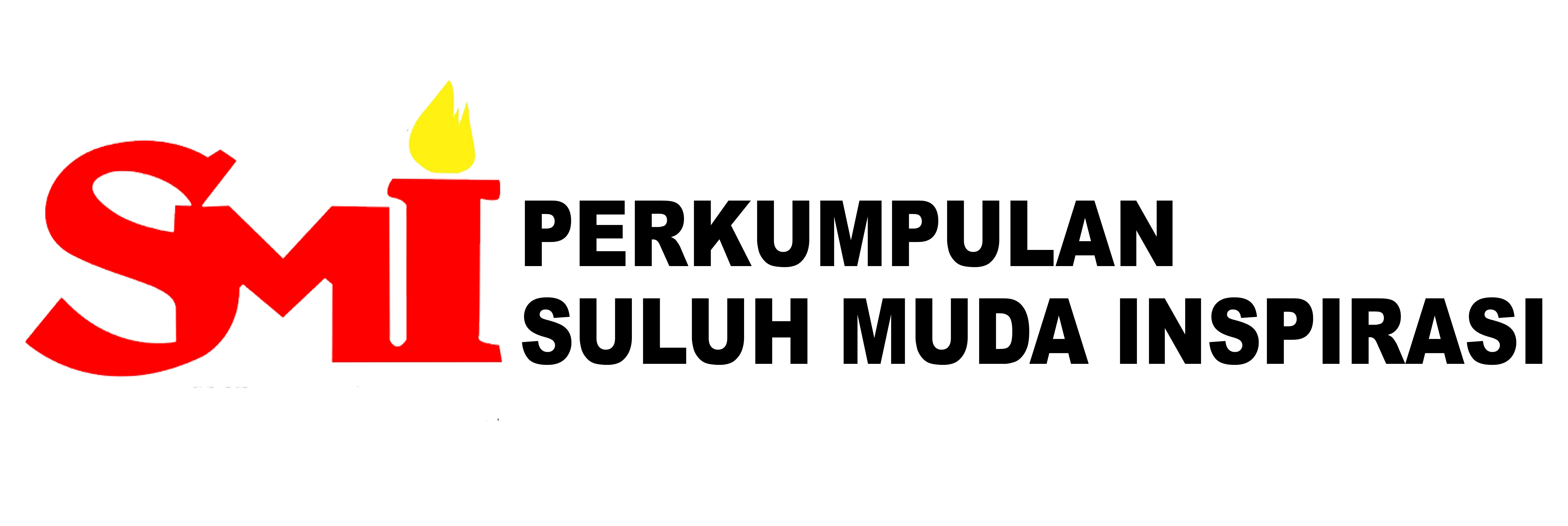Ketimpangan Ekonomi dan Politik Uang
Jumat, 24 Februari 2023
MASUKNYA kolonialisme ke Indonesia pada abad ke-16 adalah permulaan kehadiran praktek eksploitasi sumber daya alam, terutama sektor perkebunan dan sumber daya alam yang kemudian berproses mengikuti revolusi industri tahun 1830, yakni perubahan kolonialisme kuno menjadi imperialisme modern dengan yang menargetkan bahan baku dan pekerja murah.
Perubahan paradigma pada revolusi industri yang mendorong pemerintahan Belanda memberlakukan UU Agraria 1870 untuk menggunakan praktik Domein Verklaring (tanah negara) guna mengakuisisi tanah masyarakat sebagai pintu masuk pengusaha serta modal asing dari Eropa di sektor perkebunan ke nusantara.
Pembukaan Terusan Suez pada 1869, yang mempersingkat perjalanan dari Eropa ke Indonesia dan tingginya permintaan karet dunia serta komoditi perkebunan, termasuk perluasan investasi pada pertambangan dan perbankkan membuat jumlah investor asing meningkat hingga mencapai 4 miliar Gulden pada 1930.
Setelah kemerdekaan pada Agustus 1945 serta pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949, pergulatan periode transisi dari bagian kolonialisme menjadi negara merdeka menyebabkan perhatian para founding father tersita pada sistem ketatanegaraan yang agak mengabaikan penataan pada sektor ekonomi.
Investasi dan Keberlanjutan Ketimpangan Ekonomi
Kehadiran Maklumat X 1949 pada awal kemerdekaan membuat Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan multipartai, pilihan sistem yang membuat pergulatan pemerintahan disibukkan pertikaian politik yang menyebabkan jatuh bangunnya kabinet pemerintahan, bahkan ada yang hanya berumur tiga bulan, serta dipenuhi konflik politik dan militer.
Dengan berbagai kekisruhan politik pada tahun 1951 Kabinet Natsir masih mampu menghasilkan Rencana Urgensi Ekonomi dan Kabinet Wilopo membuatnya lebih rinci, dengan target pembangunan industri untuk melepaskan ketergantungan terhadap kebutuhan barang dari luar negeri.
Pada tahun 1958, Kabinet Karya di bawah PM Djuanda bersama dengan DPR mengeluarkan UU PMA (Undang-Undang Penanaman Modal Asing) No 78 tahun 1958 dengan dasar utama bahwa negara saat itu, memerlukan modal asing untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional.
Dalam UU PMA ini, perusahaan asing bisa menanamkan modal di luar industri, dengan persyaratan utama bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional, serta pembatasan pada sektor tertentu, yaitu, a. Kereta Api, b. Telekomunikasi, c. Pelayaran dan Penerbangan, d. Pembangkit tenaga Listrik, e. Irigasi dan air minum, f. Pabrik mesiu dan senjata, g. Pabrik tenaga Atom, h. Pertambangan dan bahan-bahan vital.
Selain membatasi investasi asing pada sektor strategis, pemerintah juga melakukan nasionalisasi perusahaan asing yang meliputi berbagai sektor seperti; keuangan, perdagangan, industri, pertambangan dan pertanian, yang dikuti dengan lahirnya UU No 5 tahun 1960 tentang agraria yang menghapus asas Domein Verklaring, kemudian disusul UU No. 16 tahun 1965 tentang penghentian penanaman modal asing.
Setelah kejatuhan Presiden Soekarno, pemerintahan selanjutnya sejak 1966-1998 membuka pintu investasi asing dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1967 yang mengijinkan pemodal asing memiliki saham 5 % dalam sektor strategis, dan dilonggarkan dengan UU No. 6 Tahun 1968 dimana kepemilikan saham asing bisa mencapai 49%.
Kebijakan pelonggaran berlanjut pada perpanjangan izin perusahaan asing selama 30 tahun, penghapusan persyaratan investasi sebesar US$ 1 juta pada beberapa kegiatan seperti konsultasi dan lain-lain, serta kebijakan membuka investasi asing sebagai prioritas utama untuk mendapatkan dana, selain utang luar negeri.
Pembangunan ekonomi berbasis modal asing dan SDA diteruskan dengan mengeluarkan UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 5/67 tentang Kehutanan, UU No 11/67 tentang Pertambangan, Kontrak Karya Pertambangan Generasi I dan II, UU No. 1/1967 yang berisi berbagai insentif dan jaminan kepada para calon investor asing, hingga jaminan kebijakan masa bebas pajak dan jaminan tidak adanya nasionalisasi.
Di sektor kehutanan, pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dimulai dengan terbitnya UU Kehutanan tahun 1967 dan pemberian konsesi hutan (HPH) 20 tahun kepada perusahaan penebangan kayu, yang melahirkan 301 perusahaan pemilik HPH dan 262 unit perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) menguasai 42 juta hektar hutan.
Termasuk ekspansi kelapa sawit oleh perusahaan asing dan swasta yang sangat massif, yang menurut Sawit Wacth telah mengubah komposisi kepemilikan lahan perkebunan yakni 65% dikuasai oleh korporasi dan 35% oleh non korporasi, dengan penguasaan tanah saat ini untuk perkebunan sawit mencapai 26,7 juta Ha kepada 30 group yang mengontrol ±600 perusahaan.
Padahal dari 1968 hingga 1994, CPO yang dihasilkan umumnya dari perkebunan sawit negara, namun setelah 1990-an ada perubahan kebijakan yaitu mendorong mekanisme pasar dalam investasi perkebunan, sehingga membuat Hak Guna Usaha (HGU) sangat di dominasi perusahaan swasta.
Pemberian HGU secara massif yang kemudian memunculkan persoalan seperti penyerobotan lahan ulayat, hak adat bahkan hak milik rakyat oleh pemegang HGU akibat tidak tertatanya administrasi lahan yang benar, dimana proses keluarnya ijin HGU yang sering tidak melihat keberadaan masyarakat, habitat hingga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup dan memicu resiko konflik.
Tidak jarang ditemukan pemegang HGU menggeser batas wilayah dan melakukan okupasi lahan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya konflik agraria, bahkan ditemukan Desa yang tidak bisa mempergunakan Dana Desa untuk pembangunan fisik karena terkendala hak pengelolaan antara pemegang HGU dan desa
Pada tahun 1993 pemerintah kembali memberikan insentif guna menarik PMA yang lebih besar lagi ke dalam negeri melalui Paket Deregulasi 1993 yang isinya memudahkan investor asing menanamkan modal di indonesia, disusul dengan terbitnya PP No. 20/1994 yang isinya memuat ketentuan bahwa asing sudah boleh memiliki saham mencapai 95%.
Setelah reformasi tahun 1999 pemerintah mengeluarkan perizinan kepemilikan saham perbankan untuk dikuasai asing hingga mencapai 99%, dan pada tahun 2009 khusus disektor pertambangan pembatasan kepemilikan saham asing dihilangkan dan dimungkinkannya investasi di sektor listrik dan infastruktur.
Kemudian lahirlah UU No 25 Tahun 2007 yang melindungi investor asing dari nasionalisasi dan pengambilalihan, serta memberikan hak kepada investor asing untuk mencari keadilan melalui Pengadilan Arbitrase Internasional jika bersengketa dengan pemerintah Indonesia.
Berbagai kebijakan sejak awal kemerdekaan sejatinya menjadi cermin yang mempengaruhi ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan ekonomi hingga saat ini, data Bank Dunia menyebutkan sebanyak 304 perusahaan besar di Indonesia menguasai 26 juta Ha konsesi, situasi yang menyulitkan proses pemerataan akses sumber daya atau demokrasi ekonomi.
Ketimpangan Ekonomi dan Politik Uang
Persoalan kesenjangan antara 23,7 juta petani Indonesia yang hanya memiliki total 21,5 juta Ha dibandingkan 26 juta Ha yang dimiliki 304 perusahaan, dan ± 13 juta petani yang tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan.
Data kesenjangan penguasaan sumber daya alam dan lahan tentunya adalah bagian dari kebijakan arah pembangunan ekonomi yang berlangsung lama, dan hingga kini terlihat masih mendominasi, termasuk lahirnya UU Cipta Kerja yang memasukkan kembali asas domein verklaring (tanah negara) melalui bank tanah.
Memahami asas ekonomi dalam konstitusi secara umum sejatinya demokrasi ekonomi indonesia adalah ekonomi yang memberikan peran sebesar-besarnya kepada rakyat untuk mengelola ekonomi, sesuai prinsip pasal 33 UUD 1945, yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Seperti bunyi pasal 33 ayat 2 ; “tanah, air, udara dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” melalui BUMN sebagai Badan Usaha Negara yang bekerja untuk negara dan kesejahteraan umum, termasuk menjalankan amanat UU Pokok Agraria No 5 Tahun1960 tentang penguasaan 2 Ha tanah bagi rakyat yang benar - benar mengelola tanah untuk kehidupan keluarganya.
Karena persoalan ketimpangan akses dan asset sumber daya sangat berimbas pada ketimpangan ekonomi, politik dan sosial, dimana ketimpangan ekonomi sejatinya akan menyebabkan ketimpangan pada kapabilitas dan kapasitas individu dalam dalam demokrasi politik.
Sehingga akan menyulitkan perubahan pada pokok persoalan ketimpangan yang menurut “ The Economist” adalah kapitalisme kroni yang dapat dimaknai sebagai sistem ekonomi negara yang dibangun berdasarkan pertautan pengusaha dengan penguasa, dan sangat berpotensi menyuburkan politik uang dalam demokrasi elektroral yang menganut sistem demokrasi pemilihan langsung berbiaya tinggi.