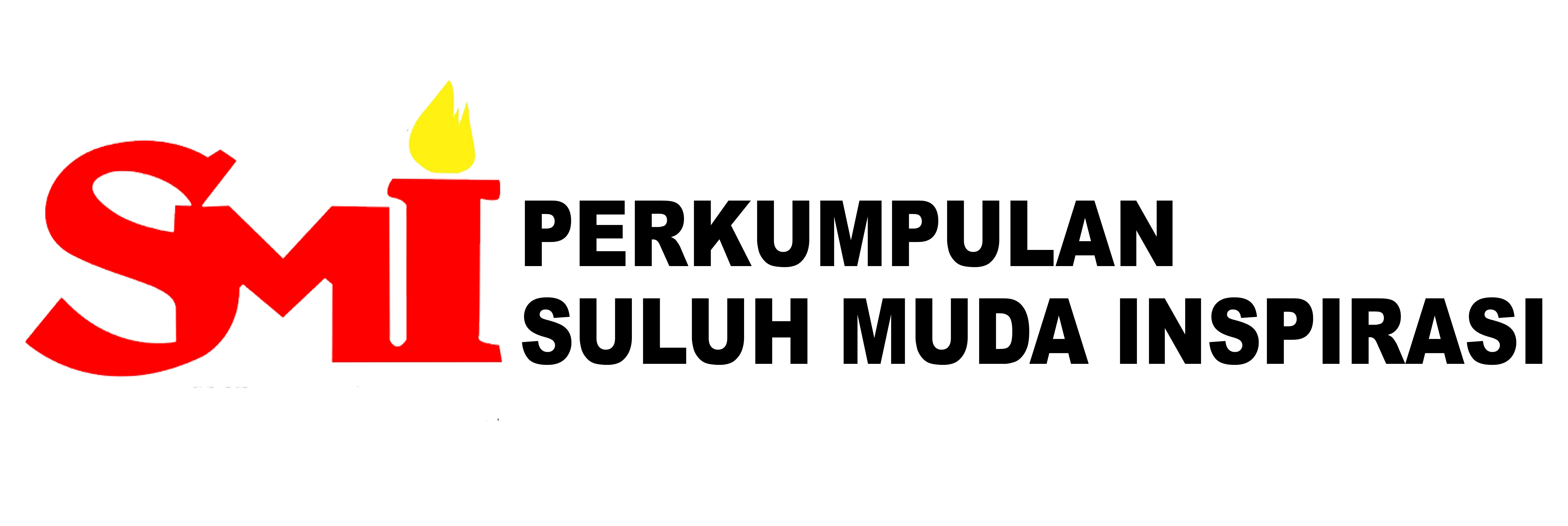Data Kemiskinan: Antara Angka dan Realita
Jumat, 02 Mei 2025
BERDASARKAN rilis pemerintah, Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sekitar 5.03 % sepanjang 2024, dan nilai ekspor-impor tetap stabil, dengan pertumbuhan angka makro ekonomi tersebut.
Pemerintah juga menyatakan angka kemiskinan yang berada di 8,7 % atau sekitar 25,22 juta, dengan menggunakan perhitungan garis kemiskinan yang dipatok BPS pada Rp 589.932 per kapita per bulan atau Rp 19.664 per hari (Maret 2024).
Jika dikonversikan dalam kebutuhan nyata pengeluaran masyarakat, maka tidak akan cukup untuk biaya sewa rumah, makan bergizi, transportasi, dan sekolah anak.
Data dari Bank Dunia justru mengkategorikan masyarakat miskin Indonesia sebesar 60,3% dari jumlah penduduk sebesar 285,1 juta jiwa pada 2024.
Penduduk miskin yang setara 171,91 juta jiwa itu didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar US$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari (kurs Rp 16.800/US$).
Karena Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto) sebesar US$ 4.580 per kapita, sehingga ukuran garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada pengeluaran US$ 6,85 per kapita per hari atau Rp 115.080 per orang per hari.
Sehingga jumlah penduduk miskin setara 60,3% dari total penduduk. Di ASEAN, Indonesia berada pada peringkat kedua setelah Laos yang sebesar 68,5%.
Perbedaan cara mengukur kemiskinan jika dilihat secara kasat mata justru lebih dekat dengan data yang disampaikan oleh Bank Dunia. Terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan tidak berpihak pada rakyat miskin.
Termasuk jika disandingkan dengan data BPS yang mencatat 7,47 juta pengangguran terbuka pada Agustus 2024, dan dari 144,64 juta penduduk bekerja pada Agustus 2024, sebanyak 57,95% di antaranya, atau setara dengan 83,83 juta orang bekerja pada kegiatan informal tanpa jaminan sosial dan ketenagakerjaan atau pekerja formal hanya 60,82 juta jiwa atau 42,05%.
Data Asosiasi Driver Online Indonesia (ADOI) dan riset Lembaga Demografi FEB UI, pada 2024 jumlah mitra ojol aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 4,7 juta orang, dimana sebagian besar berusia produktif (25–45 tahun), dan menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama
Namun, meski disebut “kemitraan,” kenyataannya driver tidak memiliki jaminan penghasilan minimum, tidak dilindungi BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis, dan tidak punya posisi tawar terhadap sistem aplikasi, driver harus menanggung sendiri biaya bensin, kendaraan, bahkan risiko kecelakaan.
Akar Kemiskinan yang Terpelihara
Dimensi kemiskinan memang sangat luas karena menyangkut ketidakberdayaan dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, dan perumahan.
Salah satunya bisa terlihat dengan banyak individu dan keluarga terkait pinjaman online yang bersifat konsumtif akibat dari ketiadaan dana darurat (berobat dan pendidikan).
Kondisi yang menjelaskan banyaknya keluarga yang terjebak lingkaran pinjaman dan utang yang tidak berujung dan membuat keluarga tersebut akan sulit keluar dari kondisi kemiskinan.
Sementara langkah yang diambil oleh pemerintah lebih didominasi kebijakan bersifat instant (bantuan), tanpa melakukan pergantian sistem dengan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kemiskinan tentunya bukan sesuatu yang muncul begitu saja, namun lahir dari berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, hingga lingkungan.
Salah satu penyebab tingginya ketimpangan dan kemiskinan yang terpelihara adalah persoalan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi sebagai akar masalah paling mendasar
Dimana sangat terlihat sejumlah kecil individu atau kelompok memiliki kendali atas sumber daya ekonomi yang signifikan, sementara mayoritas harus bertahan dengan akses yang terbatas.
Kondisi ini menciptakan siklus yang kaya semakin kaya, sementara yang tidak beruntung akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Persoalan ketidaksetaraan ini bukan hanya antar individu atau kelompok, tapi juga terlihat dari fasilitas dan infrastruktur yang berbeda antar wilayah, yang sangat berperan dalam menentukan tinggi rendahnya biaya produksi dan distribusi
Daerah atau wilayah yang tertinggal secara infrastruktur dan fasilitas akan membuat biaya produksi dan distribusi barang lebih tinggi, sehingga memicu naiknya tingkat harga (inflasi), dan berujung pada semakin tidak berdayanya golongan miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan yang berkualitas untuk keluarganya.
Ketimpangan infrastruktur dan fasilitas akses pendidikan berkualitas juga sangat berpengaruh pada kesempatan untuk meraih pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan.
Ketertinggalan di sektor pendidikan dan pengetahuan akan berdampak langsung pada terpeliharanya lingkaran kemiskinan dari generasi ke generasi berikutnya
Kondisi ini diperburuk dengan perubahan iklim serta degradasi lingkungan yang memperburuk dan menyulitkan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat yang hidup dengan mengandalkan kondisi alam seperti pertanian dan perikanan.
Selain persoalan ketidaksetaraan akses, melambatnya pertumbuhan industri dalam negeri juga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak,
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional per Maret 2024, terungkap bahwa hampir 40% dari total penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 10,04 juta adalah pekerja miskin atau bukanlah pengangguran, tapi pekerja dengan pendapatan yang sangat rendah.
Data yang mencerminkan bahwa ketersediaan pekerjaan layak yang mampu membawa pekerja menaikkan tarif hidup hingga keluar dari jerat kemiskinan, masih sangat minim, karena pekerjaan yang tersedia didominasi sektor informal yang minim memberikan akses terhadap perlindungan sosial
Melihat perkembangan Indonesia selama beberapa tahun terakhir justru mengarah pada proses deindustrialisasi. Sektor industri atau manufaktur mengalami penurunan drastis, dengan banyaknya pabrik manufaktur yang tutup dan badai PHK yang terjadi di banyak tempat.
Kondisi yang menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang kemudian dapat menelurkan sejumlah permasalahan sosial lainnya, sayangnya belum terlihat kebijakan atau penciptaan momentum untuk meningkatkan pertumbuhan lapangan pekerjaan
Padahal deindustriliasasi telah memberikan dampak semakin minimnya lapangan pekerjaan, sementara program hilirisasi pemerintah lebih berfokus pada sektor padat sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja.
Jika berkaca pada tahun 1980- an saat industriliasasi baru tumbuh di kawasan Asia dengan Jepang sebagai pionir, Indonesia pada saat itu memiliki pendapatan di atas Cina, namun kini tertinggal jauh.
China kini telah memimpin industri global, bahkan Vietnam telah meninggalkan pendapatan Indonesia.
Termasuk persoalan lulusan perguruan tinggi yang seharusnya adalah tenaga produktif siap bekerja, justru menjadi bagian penyumbang angka pengangguran, seperti menjelaskan ketiadaan roadmap vokasi nasional untuk menjawab kebutuhan kebutuhan dunia kerja.
Kondisi mismatch antara dunia pendidikan dan kerja terlihat dari data 7,4 juta orang pengangguran, sebanyak 11,28% di antaranya atau 842.378 orang merupakan lulusan D4, S1, S2, dan S3, belum lagi sarjana yang berstatus pekerja informal.
Persoalan mendasar ini kemudian bercampur dengan massifnya penyelewengan dan korupsi yang menyebabkan anggaran belanja negara menjadi tidak signifikan sebagai insentif pembangunan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat
Mengentaskan atau Memelihara Kemiskinan
Secara global evolusi program pengentasan kemiskinan terus menerus mengalami metamorforsis. Jika 1950-an dan 1960-an, investasi berupa pembangunan sarana fisik dan infrastruktur dianggap sebagai strategi melawan kemiskinan, maka pada 1970-an dipadukan dengan kebijakan yang berorientasi pada perbaikan pendidikan dan kesehatan.
Sedangkan pada 2000-an yang dikenal program SDGs (Sustainable Development Goals) yang bertumpu pada pembukaan kesempatan atau kesetaraan akses pada setiap orang, terutama masyarakat miskin dan rentan untuk mengakses pekerjaan, sarana transportasi, listrik, pasar, sekolah, air bersih, sanitasi, dan kesehatan, dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagi pembuka kesempatan.
Dengan menjadikan harmoni antara proses politik dan ekonomi melalui pengorientasian seluruh instrument negara dan multipihak untuk lebih responsif dalam pemenuhan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, terutama kesetaraan untuk memperoleh akses peningkatan kualitas SDM.
Jika mimpi besar Indonesia Emas 2045, pertanyaan sederhananya adalah bagaimana roadmapn menjadikan rakyat hidup layak, punya pekerjaan tetap yang layak dan angka ketimpangan semakin menipis.
Aau data indonesia emas hanya “kemiskinan terselubung” seperti driver ojol dan buruh harian dalam catatan pertumbuhan lapangan kerja. Sudah saatnya kebijakan berpihak pada pertumbuhan manusia bukan pada sekedar catatan angka.