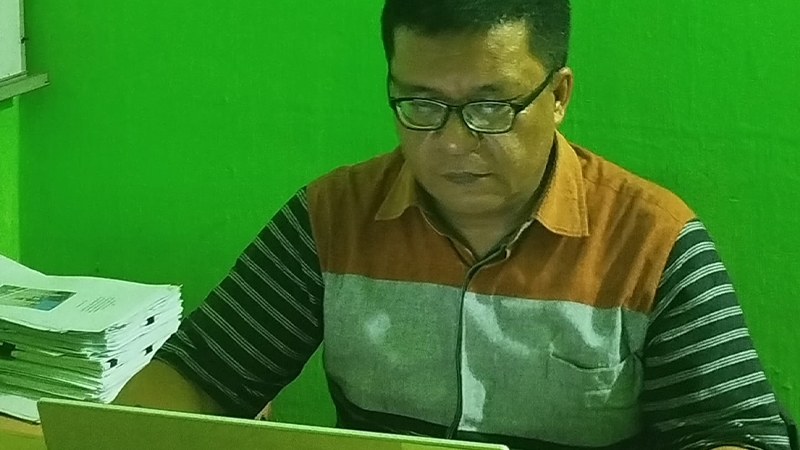Kleptokrasi di Indonesia : Negara Dirampok, Rakyat Dikorbankan
Jumat, 27 Juni 2025
“DEMOKRASI kita bisa disandera, bisa diperkosa, bisa dirusak dengan politik uang” adalah kutipan yang muncul di halaman tengah "Paradoks Indonesia", buku yang ditulis Presiden Prabowo Subianto pada 2017.
Prabowo dalam bukunya itu menyebut sebagian besar kekayaan nasional hanya mengalir ke kelompok tertentu dengan memanfaatkan proses politik dan hukum yang mudah dibeli, sehingga menyebabkan hanya 1% warga yang menikmatinya.
Indonesia menurut Prabowo sedang berada di persimpangan kritis: apakah cita-cita republik akan direbut kaum tamak atau diperjuangkan oleh mereka yang berani menjaga kepentingan rakyat banyak.
Reformasi 1998 memang meruntuhkan pemerintahan Presiden Soeharto, tetapi tidak memutus tradisi patronase. Karena sistem demokrasi dilahirkan tanpa fondasi pendanaan politik yang sehat terbangun terlebih dahulu, sehingga menyebabkan pemilu perlahan berubah menjadi “pasar modal”. Kursi eksekutif maupun legislatif tidak ubahnya seperti “pasar lelang“ bagi pemilik modal besar untuk berkompetisi.
Buku Paradoks Indonesia menyoroti paradoks ini secara tajam: negara kaya sumber daya justru mengekspor bahan mentah, membiarkan nilai tambah dan pajak hilang di luar, lalu menutup defisit dengan utang.
Ketika elite sangat bersemangat menjual konsesi tambang atau kuota ekspor minyak sawit, rakyat menanggung harga pangan mahal dan lingkungan rusak.
Kleptokrasi bukan sekadar soal amplop, ia adalah mekanisme yang memindahkan nilai ekonomi dari publik ke privat secara sistematis — dan dilegalkan melalui kebijakan.
Negara Dirampok, Rakyat Dikorbankan
Korupsi yang masif hanyalah gejala permukaan, akar persoalannya terangkai dalam tiga persoalan besar. Pertama, politik biaya tinggi: untuk menjadi bupati saja, kandidat harus menyiapkan puluhan miliar rupiah. Sponsor bisnis tentu meminta imbalan proyek, izin, ataupun pembiaran tambang ilegal.
Kedua, penegakan hukum yang selektif: sejak revisi Undang-Undang KPK 2019, lembaga antikorupsi kehilangan sebagian taring, sementara kejaksaan dan kepolisian kerap dipersepsikan rawan intervensi.
Banyak kasus kelas berat berhenti di meja mediasi kekuasaan; vonis ringan diikuti remisi berlebih membuat efek jera nyaris hilang.
Ketiga, budaya patronase yang menormalisasi suap sebagai “ongkos wajar”. Di banyak daerah, masyarakat masih menganggap kewajaran memberikan “uang terima kasih“ untuk pelayanan yang diterima, sedangkan media lokal kerap kesulitan bertahan tanpa iklan pemerintah sehingga investigasi kritis menjadi mahal.
Kombinasi ketiga persoalan yang memunculkan deretan skandal: manipulasi kuota ekspor CPO yang menyebabkan minyak goreng langka dan mahal, proyek BTS 4G yang merampok akses internet desa, sampai tata niaga timah di Bangka-Belitung yang menggerus ratusan triliun rupiah, sekaligus merusak lingkungan pesisir, dimana kerugian negara pada tahun 2024 ditaksir menembus Rp 310 triliun.
Berbagai persoalan diatas tentunya bukan kebetulan dan bukan sekadar “oknum”, tapi merupakan bagian dari sistem yang sistematis: sebuah rezim yang memungkinkan uang negara dijarah secara sah oleh yang punya kuasa.
Itulah kleptokrasi: kondisi di mana negara dijalankan oleh dan untuk pencuri berseragam.
Kleptokrasi berasal dari bahasa Yunani: klepto (mencuri) dan kratos (kekuasaan) yang bukan sekadar soal seorang pejabat yang menerima suap, namun sistem pemerintahan di mana pejabat tinggi, pengambil kebijakan, hingga pemilik modal bekerja dalam satu kongsi: menyedot kekayaan negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Yang membedakan kleptokrasi dari sekadar korupsi adalah skala dan keberlanjutannya. Dalam kleptokrasi, praktik-praktik tersebut bukan penyimpangan, tetapi sudah menjadi cara kerja utama.
Bahkan, hukum, kebijakan, dan anggaran disusun untuk mendukung keberlangsungannya. Dengan kata lain, pencurian dilembagakan dan diformalisasi.
Walaupun pasca reformasi Indonesia berupaya membangun sistem demokrasi, dengan pembentukaan lembaga antikorupsi, keterbukaan informasi diperluas, dan media bebas tumbuh, tapi sayangnya akar-akar kleptokrasi masih mencengkeram kuat di seluruh lapisan kekuasaan.
Demokrasi memang hadir, tetapi ia tersandera oleh politik uang, transaksi kekuasaan, dan kontrol elite terhadap sumber daya negara.
Kondisi yang bukan semata akibat dari mental pejabat yang rakus atau integritas individu yang rapuh, tapi adalah persoalan struktural, sistem pemilu yang sangat mahal dan lemahnya akuntabilitas publik menciptakan insentif untuk mencuri, bukan melayani.
Menurut banyak studi, dana yang dibutuhkan untuk menjadi anggota legislatif di tingkat nasional bisa mencapai Rp 5–25 miliar per orang.
Di tingkat daerah, biayanya mungkin lebih rendah, tetapi tetap signifikan. Dalam sistem seperti ini, sulit membayangkan seorang kandidat akan murni mengandalkan idealisme. Uang harus datang dari sponsor, dan sponsor pasti menuntut balas jasa.
Siklusnya sederhana namun mematikan: uang digunakan untuk membeli suara, kekuasaan digunakan untuk balas budi, proyek dikorupsi untuk mengembalikan modal. Dalam proses ini, kepentingan publik digadaikan demi keuntungan kelompok kecil.
Laporan dari Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa sepanjang 2024, ada lebih dari 2.000 perkara korupsi yang ditindak. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp 300 triliun.
Kasus-kasus besar seperti korupsi timah di Bangka Belitung, proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo, dan manipulasi kuota ekspor minyak sawit adalah contoh bagaimana praktik kleptokrasi tidak hanya mencuri uang, tapi juga merusak pasar, lingkungan, dan stabilitas sosial.
Kleptokrasi juga melahirkan ketimpangan. Di negeri yang konon demokratis ini, 10 persen kelompok terkaya menguasai lebih dari 77 persen aset finansial nasional.
Kesejahteraan rakyat jalan di tempat, sementara para elit politik–ekonomi hidup mewah tanpa malu. Ini bukan semata-mata persoalan ekonomi, tapi soal keadilan sosial yang diinjak-injak di depan mata.
Termasuk proses penindakan korupsi yang dipolitisasi, dimana banyak kasus besar berhenti di level pelaku menegah dan tidak menyentuh akar permasalahan.
Hukum sering tajam ke lawan politik, tetapi tumpul ke pihak yang punya kedekatan dengan kekuasaan. Publik menyaksikan ini dengan frustrasi, lalu pelan-pelan kehilangan kepercayaan.
Kelemahan institusi hokum diperparah oleh minimnya partisipasi publik. Banyak daerah tidak punya jurnalis investigasi, tidak punya pemantau anggaran, dan masyarakatnya pun masih menganggap pejabat sebagai “raja kecil” yang tak bisa digugat, maka kleptokrasi tumbuh subur: ketika pengawasan mati, kekuasaan menjadi mutlak.
Menemukan Akar Penyelesaian
Membasmi kleptokrasi jelas tidak bisa dilakukan semalam, tapi membutuhkan perubahan dari hulu ke hilir, dari sistem ke budaya, dari elite ke rakyat, dengan beberapa langkah mendesak
Pertama, adalah reformasi pendanaan politik, dimana Negara harus menyediakan dana kampanye yang cukup bagi partai dan kandidat, transparansi sumbangan politik harus diwajibkan dan pengusaha tidak boleh menyumbang, agar uang tidak terus menjadi penentu utama siapa yang menang dan siapa yang berkuasa.
Kedua, independensi dan integritas semua lembaga penegak hukum harus dimurnikan, dimana lembaga dan aparat hukum harus dipulihkan orientasinya pada ketertundukan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, bukan tekanan politik atau uang, dimulai dari penempatan jabatan dan penyidik tidak boleh menjadi bagian dari kompromi politik atau kedekatan.
Ketiga, digitalisasi tata kelola. Setiap kontrak proyek, sumber dana, jadwal pelaksanaan, hingga foto progres wajib diunggah ke platform terbuka seperti sistem e-procurement.
Teknologi blockchain bisa diterapkan pada rantai pasok komoditas strategis — timah, nikel, CPO — agar tiap ton produksi dapat dilacak hingga pelabuhan ekspor.
Transparansi yang radikal akan menutup ruang manipulasi sekaligus memudahkan warga dan media melakukan audit sosial.
Keempat, revolusi budaya integritas. Pendidikan antikorupsi tidak cukup berhenti pada hafalan slogan; ia harus dilatih lewat praktik.
Siswa sekolah diwajibkan belajar mengelola kas kelas dengan laporan terbuka, mahasiswa diwajibkan proyek audit dana kemahasiswaan, aparatur sipil menjalani tes gaya hidup rutin.
Pemimpin yang terjerat skandal harus mundur tanpa menunggu proses hukum usai, agar tercipta standar malu di ruang publik.
Kelima, partisipasi warga sebagai penentu. Aplikasi pelaporan seperti SP4N-Lapor! sudah ada, tetapi efeknya bergantung pada keberanian masyarakat memakai.
Setiap pungutan liar yang diunggah dan diviralkan menciptakan tekanan politik lebih kuat dibanding seribu pasal perundang-undangan.
Kebiasaan menolak amplop kampanye, memotret papan proyek, dan mengajukan permohonan informasi publik secara kolektif dapat mempersempit ruang gerak kleptokrat hari demi hari.
Kleptokrasi bukan kutukan abadi. Banyak negara pernah mengalami fase gelap ini dan berhasil keluar—dengan reformasi menyeluruh, tekanan publik yang konsisten, dan perubahan budaya, karena republik ini belum selesai dan tidak boleh kalah, seperti kata penyair: negara yang lahir dari perjuangan rakyat tidak boleh dibiarkan jatuh ke tangan pencuri.
Paradoks Indonesia mengingatkan bahwa bangsa ini kaya, tetapi bisa miskin bila dibajak segelintir orang. Kleptokrasi menampakkan wujudnya ketika politik dipasarkan, hukum dinegosiasikan, dan rakyat dibiarkan pasrah.
Penulis Penggiat HAM dan Demokrasi